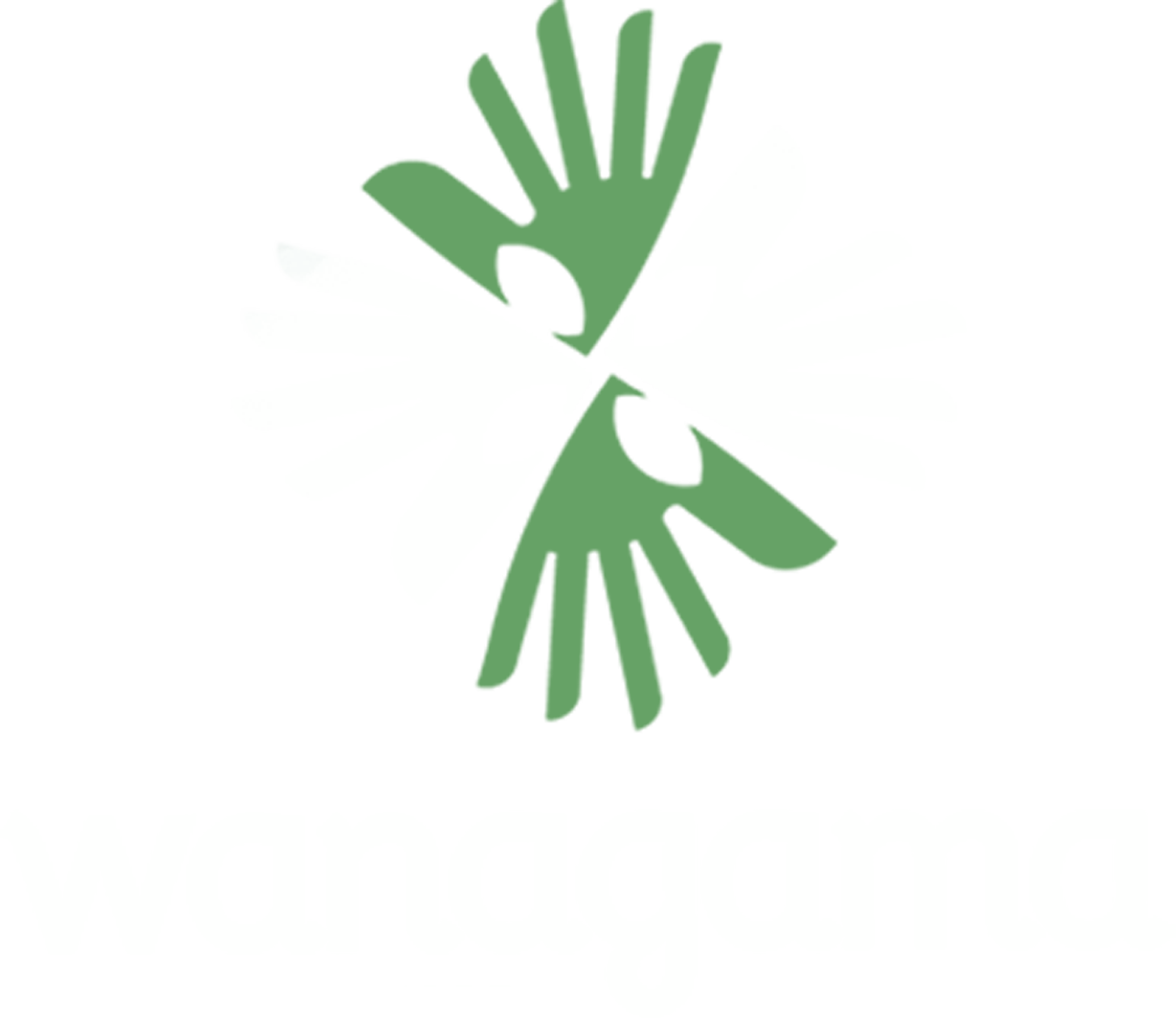Halo Sahabat Wanagama!
Kembali lagi dengan update mingguan “Tahukah kamu” Website Wanagama!
Kemarin kita sudah mempelajari banyak tanaman, kali ini kita akan mempelajari tentang hewan yang dulu pernah berjasa dalam pembangunan Wanagama. Ada yang tau??? Yap, ULAT SUTERA. Si kecil yang mahal ini menjadi salah satu agen perintis Hutan Wanagama loh! Bagaimana bisa? Yuk ikuti penjelasan kali ini
Sebelum kita cerita tentang sejarah Ulat Sutera di Wanagama, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih dengan Ulat Sutera secara general.